Hustle culture sempat menjadi perbincangan di media sosial. Elon Musk adalah salah satu pengusaha yang dianggap oleh warganet menerapkan budaya itu.
Di Twitter atau X, Musk mencuitkan bahwa 40 jam per minggu belum cukup untuk membuat perubahan:
“There are way easier places to work, but nobody ever changed the world on 40 hours a week.”

Kerja keras CEO SpaceX dan Tesla Inc. tak terbantahkan. Dari sisi kekayaan, Forbes mencatat kekayaan Musk sebesar USD306,5 miliar atau setara Rp4.386 triliun pada 2021.
Prinsip Musk mengilhami pekerja untuk melakukan hustle culture. Mereka termotivasi untuk bekerja melebihi batas waktu jika ingin berhasil seperti miliarder dunia.
Tidak salah jika seseorang termotivasi oleh Musk dan produktivitasnya meningkat.
Namun, HR dan manajer harus menyadari bahwa hustle culture menciptakan lingkungan kerja yang tidak sehat. Dan, setiap orang memiliki standar hidup berbeda.
Memahami Hustle Culture
Kita harus mengakui bahwa ada orang-orang yang mengglorifikasi hustle culture.
Seseorang yang berada di lingkungan hustle culture akan mengikuti budaya untuk bekerja berjam-jam (lebih dari jam kerja yang telah ditentukan) dan sering kali melelahkan.
Bila tidak melakukannya, ia akan dianggap aneh, dibanding-bandingkan dengan rekan kerja lain, dan dipandang tidak loyal terhadap perusahaan. Bagi mereka, budaya kerja hiruk pikuk telah menjadi norma.
Apa itu hustle culture?
Shamani Joshi, penulis Vice, menuliskan hustle culture didasarkan pada keyakinan bahwa seseorang hanya bisa berhasil dalam hidup jika memaksakan diri sampai mengorbankan siklus tidur dan kewarasannya.
Budaya ini sering diplesetkan menjadi ‘kesibukan tak pernah berhenti’ atau ‘kerja keras, rekening Anda terlihat seperti nomor telepon’. Oleh sebab itu, hustle culture diartikan sebagai bentuk workaholism ekstrem.
Di India, di mana 1,3 miliar penduduk memperebutkan peluang dan sumber daya, mereka menjalankan hustle culture menjadi budaya yang sangat beracun ketika bekerja.
Pandemi memengaruhi hustle culture
Sebelum pandemi COVID-19, ada tipe pekerja yang ingin menyibukkan diri dan terdorong untuk bekerja lebih keras.
Saat pandemi datang, hampir semua sisi kehidupan berjalan lambat. Hal itu membuat mereka mempunyai waktu untuk merenungkan gaya hidup yang mereka jalani.
Arushi Sethi, aktivis dan pendiri Trijog (jasa konseling mental health), mengatakan bahwa kita telah melewati lima fase pandemi.
Pertama, honeymoon phase. Fase pertama mendorong kita untuk mengeksplorasi diri secara kreatif, seperti membuat kopi dalgona dan memanggang garlic bread.
Kedua, stres. Fase di mana seseorang belum merasakan ada masalah berarti.
Ketiga, stres kronis. Fase ini menyebabkan motivasi menurun dan sulit untuk merasa optimis.
Keempat, burnout (kelelahan). Fase yang membuat seseorang mulai meragukan diri sendiri ke kondisi normal.
Ia merasa gagal memenuhi kebutuhan pribadi. Ia juga mengalami kekosongan dan memandang pesimistis pada kehidupan kerjanya.
Kelima, habitual burnout (kelelahan karena kebiasaan). Fase terakhir ini akan memicu kemarahan, kegelisahan, dan tekanan pada diri seseorang. Ia bisa gagal mengenali emosi dan perlu berhenti sejenak untuk mengatasinya.
4 Dampak Di Balik Hustle Culture
“Banyak orang mengatakan hal-hal seperti, ‘Rekan kerja saya mengirim email pada pukul 03.00, jika mereka bekerja, mungkin saya harus bekerja’,” ujar Dr. Jeanne Hoffman, psikolog di Departemen Kedokteran Rehabilitasi di Fakultas Kedokteran University of Washington (UW).
Menurut Dr. Hoffman, hal itu adalah budaya orang Amerika. Mereka bekerja jauh lebih banyak dan memiliki lebih sedikit waktu istirahat daripada negara lain.
Saat seseorang berada dalam hustle culture, selalu ada pekerjaan yang harus diselesaikan dan tenggat waktu yang wajib dipenuhi. Tak peduli berapa waktu telah dihabiskan atau pencapaian yang ia lakukan.
Catatan yang perlu Anda pertimbangkan adalah bekerja lebih dari 50 jam per minggu tidak mendorong kreativitas.
Hal itu justru menyebabkan Anda kurang produktif dan lebih sering sakit. Sederhananya, hustle culture membahayakan diri Anda.
1) Karyawan burnout
Apakah saat ini Anda baik-baik saja atau merasa sangat lelah? Cukup tidur?
Masih bisa bekerja dengan baik dan mencapai target? Bagaimana hubungan Anda dengan orang terdekat?
Tak masalah jika Anda dalam kondisi tidak baik. Terkadang seseorang mengalami burnout akibat sibuk mengerjakan proyek besar selama berbulan-bulan.
Dr. Anne Browning, Direktur Pendiri UW Resilience Lab, mengatakan karyawan burnout kesulitan untuk mengelola maupun mengerjakan tugas dasar di kantor.
Namun, tanda kelelahan dapat muncul berbeda pada masing-masing karyawan. Misalnya, memerlukan usaha untuk bangun dari tempat tidur, sulit konsentrasi, atau mudah marah karena hal sepele.
2) Toxic productivity
Bahaya hustle culture yang sering tidak disadari adalah toxic productivity. Produktivitas beracun ini bersembunyi atas nama kepositifan.
Toxic productivity terjadi ketika Anda tak memedulikan seberapa produktif diri sendiri, tetapi selalu merasa bersalah karena tidak melakukan lebih banyak pekerjaan. Kondisi itu akan mengabaikan asupan nutrisi dan waktu istirahat.
3) Masalah kesehatan mental dan fisik
Bekerja lembur hingga “terserang” burnout dikaitkan dengan risiko kesehatan, baik mental maupun fisik.
Masalah tersebut adalah tekanan darah tinggi, detak jantung tidak teratur, penyakit kardiovaskular, dan depresi. Jika hal ini diabaikan, kondisi kesehatan akan memburuk dan memengaruhi produktivitas kerja.
4) Menciptakan lingkungan kerja tidak sehat
Tak masalah jika Anda berlomba-lomba meningkatkan kinerja dengan rekan satu tim.
Satu hal yang perlu diperhatikan ketika “perlombaan” itu berubah menjadi lingkungan kerja tidak sehat. Misalnya, mencuri ide, memfitnah, bergosip, dan lainnya.
Peran HR Menghadapi Hustle Culture
Budaya kerja serba hiruk pikuk bukan persoalan karyawan saja. Jika perusahaan menginginkan lingkungan dan tenaga kerja sehat, maka hal ini adalah urusan semua pihak, termasuk manajemen, tim HR, dan manajer.
1) Menetapkan batasan
Ketika karyawan berada dalam kondisi burnout karena hustle culture, tim HR bersama manajemen dan manajer dapat menetapkan batasan kerja. Misalnya, semua kegiatan yang berurusan dengan pekerjaan harus dilakukan pada jam kerja, termasuk pengiriman email atau pesan singkat.
Duroflex, perusahaan manufaktur tempat tidur asal India, sangat ketat dalam menerapkan jam kerja. Salah satunya adalah tidak mengirimkan pesan kerja kepada karyawan sebelum pukul 09.00 dan setelah 21.00.
2) Waktu istirahat
Tim HR dapat mendorong karyawan untuk menikmati waktu istirahat, seperti menggunakan istirahat makan siang, mengambil cuti untuk berlibur, atau memiliki me time di akhir pekan.
Dr. Hoffman menjelaskan bahwa memiliki waktu pribadi dapat menjaga batasan antara pekerjaan dan waktu luang. Cara tersebut akan meminimalisir karyawan untuk bekerja lembur.
3) Membangun ketahanan
Ini bukan membuat Anda bertahan dalam hustle culture. Dr. Browning mengatakan tiga kunci ketahanan adalah terkoneksi, bersyukur, dan memiliki tujuan.
Tim HR dapat mengajak karyawan fokus pada alasan bekerja, mengingatkan makna di balik pekerjaan, merefleksikan hubungannya bersama rekan setim, serta berhasil melewati hari-hari sulit.
4) Work-life balance
HR juga berperan mempromosikan work-life balance di lingkungan kantor.
Anda dan tim dapat mempersilakan karyawan istirahat (di luar jam istirahat) setelah berkutat dengan pekerjaan intensitas tinggi, mendengarkan musik, mengobrol dengan rekan setim HR di pantry.
5) Memberikan ruang aman
Bercerita atau mengeluarkan keluh kesah dengan rekan kerja dapat meringankan beban seseorang. Tak ada salahnya jika HR memberikan ruang aman untuk mendengarkan cerita karyawan.
Jika mereka membutuhkan bantuan, bantu sesuai kapasitas HR. Kalau masalah mereka cukup berat, Anda bisa merekomendasikannya untuk konsultasi ke profesional.
Penutup
Bekerja keras untuk meningkatkan produktivitas merupakan langkah positif yang layak dihargai.
Namun, pastikan diri Anda dalam kondisi sehat secara mental dan fisik serta bahagia. Kalau bukan Anda yang merawat diri Anda sendiri, lalu siapa?
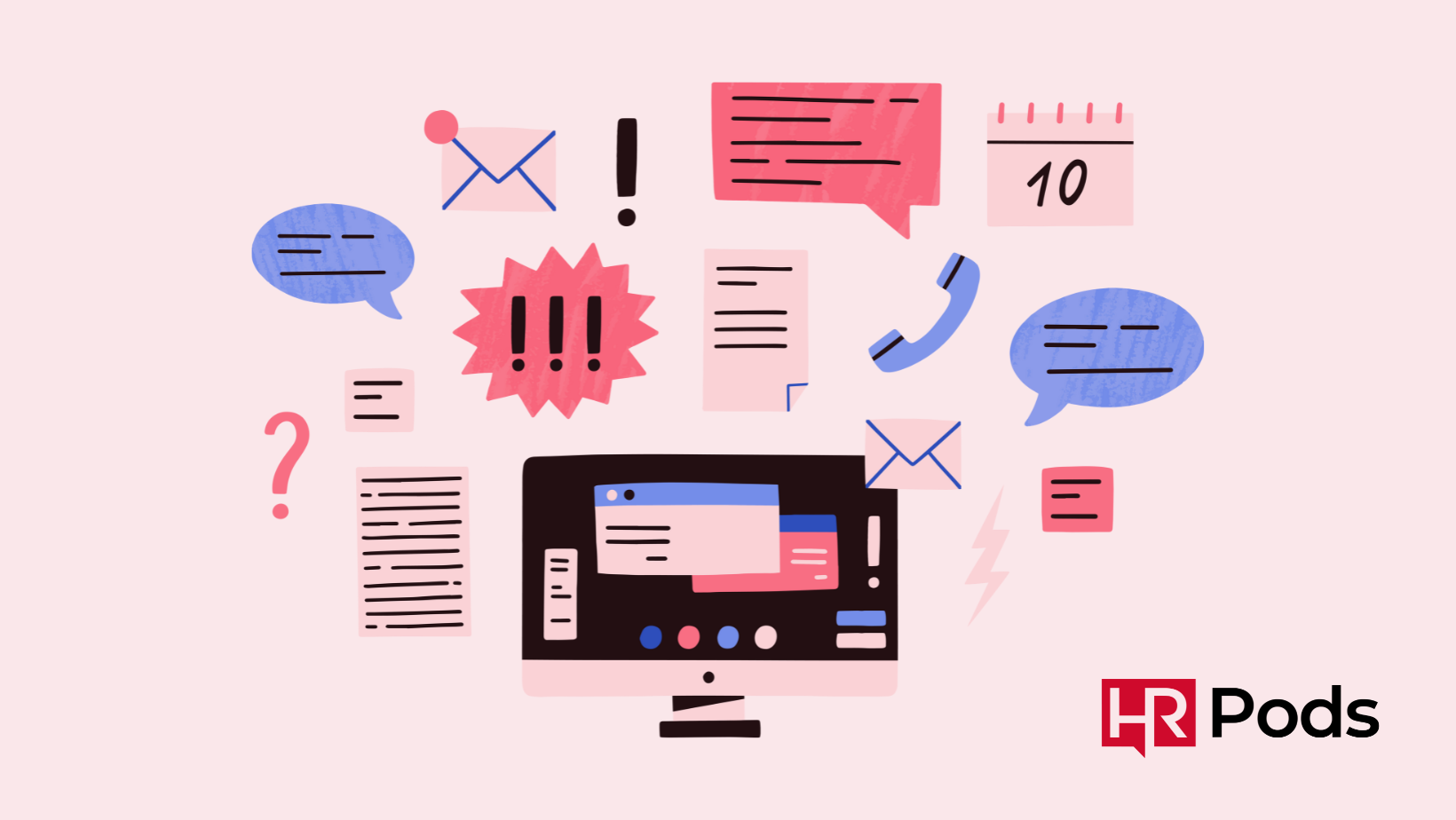
Leave a Reply